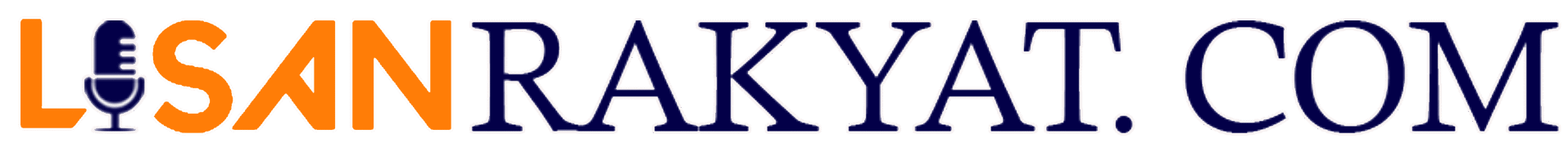Oleh : Madyatama SY Failisa, Anggota Mapala Reksa Wana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Ketika “Serambi Madina” Berhadapan dengan Ambiguitas Moral Negara Daerah
Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penyelenggaraan Tempat Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Pohuwato tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan teknis administratif. Ia justru membuka ruang refleksi yang lebih mendalam tentang bagaimana negara daerah memaknai otonomi, identitas kolektif, dan fungsi hukum dalam masyarakat yang secara historis dan kultural menjadikan agama sebagai fondasi kehidupan publik.
Gorontalo selama ini dikenal dengan sebutan Serambi Madina, sebuah identitas simbolik yang berakar pada falsafah adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah. Falsafah ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan kerangka etik yang mengatur relasi sosial, politik, dan hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum daerah seharusnya tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga selaras secara moral dengan nilai kolektif tersebut.
Masalah muncul ketika perda ini justru memperlihatkan sikap negara daerah yang ragu: ingin tampak modern dan netral, tetapi hidup di tengah masyarakat yang menuntut kejelasan nilai. Ambiguitas inilah yang membuat perda ini problematik secara filosofis.
Otonomi Daerah dan Keberanian Mengekspresikan Nilai: Salah Kaprah atas Pasal 18 Ayat (6)
Dasar normatif pembentukan peraturan daerah sering kali dirujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Namun dalam praktik, ketentuan konstitusional ini kerap dipahami secara sempit dan teknokratis—seolah-olah otonomi daerah hanya menyangkut pembagian kewenangan administratif, bukan ekspresi nilai dan identitas lokal.
Pemahaman semacam ini merupakan salah kaprah konstitusional. Pasal 18 ayat (6) tidak berdiri di ruang hampa nilai. Ia lahir dari semangat desentralisasi pasca-reformasi yang bertujuan mengoreksi sentralisme negara, sekaligus mengakui keberagaman sosial, budaya, dan moral daerah-daerah di Indonesia. Dengan demikian, hak daerah membentuk perda bukan sekadar hak mengatur, tetapi juga hak mengartikulasikan pandangan hidup masyarakatnya dalam hukum.
Jika otonomi dimaknai hanya sebagai kewenangan prosedural yang harus “aman” secara administratif dan netral secara moral, maka Pasal 18 ayat (6) direduksi menjadi legitimasi desentralisasi anggaran dan birokrasi, bukan desentralisasi nilai. Padahal, dalam negara majemuk seperti Indonesia, justru nilai lokal itulah yang menjadi sumber legitimasi sosial dari hukum daerah.
Dalam konteks Gorontalo, yang secara historis dan kultural dikenal dengan falsafah Serambi Madina—adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah—agama tidak pernah ditempatkan sebagai urusan privat semata. Ia menjadi fondasi etika publik dan rujukan moral kolektif. Oleh karena itu, ketika negara daerah memilih bersikap “netral nilai” dengan dalih kehati-hatian konstitusional, negara justru menanggalkan sumber legitimasinya sendiri.
Netralitas semacam ini bukanlah kebajikan konstitusional, melainkan ketakutan normatif. Negara daerah tampil rasional dan aman di atas kertas, tetapi secara sosial menjadi asing dan berjarak dari masyarakatnya. Hukum memang sah secara formal, tetapi miskin penerimaan kultural. Ironisnya, perda pengendalian hiburan malam di Pohuwato justru memperlihatkan kontradiksi ini: ia dibenarkan atas nama Pasal 18 ayat (6), tetapi gagal memanfaatkan pasal tersebut sebagai ruang keberanian nilai. Negara daerah memilih jalan tengah yang tampak netral, padahal dalam masyarakat religius, netralitas justru dibaca sebagai ketidakberpihakan terhadap nilai kolektif.
Dengan demikian, persoalan perda ini bukan terletak pada kekurangan dasar konstitusional, melainkan pada cara keliru memahami konstitusi itu sendiri. Pasal 18 ayat (6) seharusnya dibaca sebagai mandat untuk menghadirkan hukum daerah yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga legitim secara moral dan kultural.
Definisi yang Sejak Awal Bersifat Permisif
Ambiguitas pemahaman otonomi tersebut tercermin sejak awal dalam konstruksi definisi Perda, khususnya Pasal 1 angka 9, angka 11, dan angka 13. Definisi hukum tidak pernah netral; ia selalu membawa pesan normatif tentang apa yang dianggap wajar dan dapat diterima.
Pasal 1 angka 9 mendefinisikan hiburan malam sebagai usaha penyedia tempat bersantai “dengan atau tanpa pramuria”. Istilah pramuria secara sosiologis hampir selalu identik dengan perempuan dan dalam praktik industri hiburan malam merepresentasikan komodifikasi tubuh perempuan sebagai bagian dari mekanisme pasar. Ketika istilah ini dilegalkan dalam bahasa hukum, negara tidak lagi sekadar mengakui realitas, tetapi mengajarkan penerimaan normatif atas objektifikasi perempuan.
Logika ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 11 tentang karaoke “dengan atau tanpa pemandu lagu” serta Pasal 1 angka 13 yang menormalkan operasional kelab malam hingga dini hari dengan minuman beralkohol. Keseluruhan definisi ini membentuk satu kesatuan logika: negara daerah tidak sedang membatasi praktik hiburan malam, melainkan menatanya sebagai industri yang sah. Hal ini justru menjatuhkan marwah hukum itu sendiri, sebab hukum berubah menjadi instrumen normalisasi praktik yang problematik secara moral.
Mengelola Risiko, Bukan Menilai Praktik: Negara Mengakui Dampak, Menghindari Akar Persoalan
Paradoks kebijakan perda ini tampak paling jelas dalam Pasal 4, yang mewajibkan penyelenggara tempat hiburan dan rekreasi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja sedikitnya empat kali dalam setahun. Ketentuan ini bukan norma teknis yang netral, melainkan pengakuan implisit negara daerah atas adanya risiko kesehatan serius yang melekat pada praktik hiburan malam, khususnya yang berkaitan dengan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.
Pencantuman pasal ini menunjukkan bahwa negara daerah menyadari kerentanan biologis dan sosial dari praktik yang diaturnya. Namun persoalan utamanya bukan pada kesadaran tersebut, melainkan pada pilihan kebijakan yang diambil setelah risiko diakui. Negara tidak menggunakan pengakuan ini sebagai dasar untuk menilai praktik hiburan malam secara normatif, melainkan memilih pendekatan mitigatif yang bersifat teknis-medis.
Dengan demikian, hukum direduksi menjadi instrumen manajemen risiko. Praktiknya dibiarkan, selama dampaknya dapat dikendalikan melalui prosedur kesehatan. Jika suatu praktik diakui memiliki risiko serius terhadap martabat manusia dan ketahanan sosial, maka praktik tersebut semestinya menjadi objek penilaian moral, bukan sekadar pengelolaan teknis.
Tabrakan Norma dalam Pengaturan Ramadan: Simbol Religius tanpa Kejelasan Sikap
Ambiguitas nilai dalam perda ini mencapai titik paling nyata dalam Pasal 8, khususnya pada huruf a dan huruf b, yang secara normatif saling menegasikan. Pasal 8 huruf a mengatur jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan, sementara Pasal 8 huruf b justru menyatakan penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan.
Dua ketentuan ini tidak dapat dipertahankan secara logika hukum. Jika tempat hiburan malam ditutup selama Ramadan, maka pengaturan jam operasional menjadi tidak relevan. Sebaliknya, jika jam operasional masih diatur, maka klaim penutupan menjadi semu. Tabrakan norma ini bukan sekadar kesalahan redaksional, melainkan cerminan kebingungan konseptual negara daerah dalam memosisikan nilai agama.
Ramadan dalam masyarakat Gorontalo bukan hanya peristiwa kalender, melainkan ruang sakral etika publik. Ketika negara daerah tidak berani memilih antara penutupan normatif atau pembatasan administratif, hukum akhirnya jatuh pada simbolisme kosong: tampak religius di permukaan, tetapi ragu dalam sikap.
Alih-alih menjadikan Ramadan sebagai dasar larangan normatif yang tegas, perda ini justru menampilkan pendekatan kompromistis yang memperlakukan nilai agama sebagai variabel pengaturan waktu, bukan sebagai sumber hukum. Inilah bentuk paling jelas dari kehilangan arah moral dalam kebijakan daerah.
Penutup: Serambi Madina atau Sekadar Nama?
Perda Pengendalian Tempat Hiburan Malam di Pohuwato pada akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih besar dari sekadar tata kelola hiburan: krisis keberanian normatif negara daerah. Hukum dipilih untuk merapikan konsekuensi, tetapi enggan menyentuh akar nilai. Negara daerah ingin terlihat tertib, tetapi takut terlihat berpihak.
Dalam konteks daerah yang menyebut dirinya Serambi Madina, sikap ini bukanlah kehati-hatian, melainkan pengingkaran halus terhadap falsafahnya sendiri. Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah kehilangan daya ikat ketika tidak berani diterjemahkan sebagai arah kebijakan, melainkan hanya dijadikan simbol identitas kultural.
Otonomi daerah tidak lahir untuk memproduksi hukum yang aman secara administratif, tetapi kosong secara moral. Ia hadir untuk memberi ruang bagi daerah mengekspresikan nilai hidup masyarakatnya ke dalam hukum positif. Ketika ruang itu tidak digunakan, otonomi berubah menjadi sekadar desentralisasi kewenangan tanpa jiwa.
Karena itu, yang dibutuhkan ke depan bukan sekadar revisi teknis perda, melainkan keberanian menyusun arsitektur kebijakan yang jujur: menempatkan nilai agama sebagai tujuan, regulasi sebagai alat. Tanpa desain itu, pengendalian hanya akan menjadi normalisasi yang dilegalkan. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah Serambi Madina ingin hidup sebagai nilai yang mengatur, atau cukup sebagai nama yang dipajang? Di titik inilah hukum daerah diuji bukan oleh pasal-pasalnya, tetapi oleh keberaniannya memilih nilai.